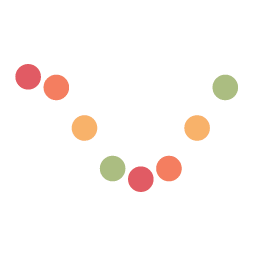Di Sektor Ketenagakerjaan, Ini Catatan Kritis Civitas FH UGM Terhadap RUU Cipta Kerja

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengungkapkan pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja. Sikap itu tertuang dalam policy paper bertajuk "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja".
Tim penyusun policy paper tersebut terdiri dari Prof. Sigit Riyanto, Prof. Maria S.W Sumardjono, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, Prof. Sulistiowati, Prof. Ari Hernawan, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. Totok Dwi Diantoro, Dr. Mailinda Eka Yuniza, I Gusti Agung Made Wardana Ph.D, dan Nabiyla Risfa Izzati LL.M. Berdasarkan dokumen policy paper yang KONTAN peroleh, Jumat (13/3), tim FH UGM membahas 11 bidang yang dirumuskan dalam RUU Cipta Kerja.
Salah satu bidang yang dibahas adalah ketenagakerjaan. Berikut ini isi policy paper tim FH UGM yang mengkritisi rumusan pengaturan bidang ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja lebih fokus pada tujuan peningkatan ekonomi, dan abai terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pasal 88 RUU Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan pengaturan baru yang diatur dalam RUU bertujuan menguatkan perlindungan dan meningkatkan peran tenaga kerja dalam mendukung ekosistem investasi.
Hal ini menguatkan paradigma developmentalisme yang cukup sentral dalam RUU ini, yang mana tersirat bahwa investasi dan pembangunan ekonomi merupakan hal paling utama dalam pembangunan suatu negara.
Sebagian besar peraturan yang diubah dalam RUU ini banyak berbicara mengenai efisiensi dan peningkatan produktifitas tenaga kerja, namun RUU ini justru tidak mengubah atau membuat peraturan baru yang berkaitan dengan pelatihan kerja atau peningkatan kompetensi pekerja.
Padahal, berbicara mengenai penciptaan lapangan kerja seharusnya justru berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja.
Alih-alih perlindungan pekerja, RUU Cipta Kerja justru berpotensi membuat pasal ketenagakerjaan kembali terpinggirkan, tergerus oleh kebutuhan investasi dan ekonomi. Padahal, dalam hubungan industrial Pancasila, perlindungan pekerja merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah.
Beberapa catatan lebih lanjut dalam bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya Ketentuan yang Perlu Diatur Lebih Lanjut
Ada banyak pengaturan di RUU Cipta Kerja yang harus diterjemahkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah.
Pada bab ketenagakerjaan, terdapat 17 (tujuh belas) ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, dan 2 (dua) ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Artinya, dapat dikatakan bahwa Rancangan Undang-Undang ini tidak menyelesaikan masalah hiper-regulasi.
2. Penghapusan Batas Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang tadinya terbatas untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun,13 menjadi tidak dibatasi oleh Undang-Undang sebagaimana tertera dalam Pasal 56 ayat (3) UU a quo.
Dengan demikian secara tidak langsung RUU Cipta Kerja menghapuskan pembatasan waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan menyerahkannya pada kesepakatan para pihak. Artinya, peran pemerintah menjadi lemah, karena tidak dapat mengintervensi jangka waktu PKWT.
Hal ini dilanjutkan dengan dihapuskannya ketentuan mengenai kemungkinan perubahan PKWT menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/perjanjian kerja tetap), yang mana output dari ketentuan ini akan menyebabkan semakin menjamurnya jenis pekerja kontrak.
Ketentuan ini sudah banyak dikritik oleh kalangan pekerja karena menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pekerja.
3. Aturan Alih Daya yang Ganjil
RUU menghapuskan Pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan namun tetap mempertahankan Pasal 66. Penghapusan pasal tersebut menekankan alih daya atau outsourcing masih diperbolehkan oleh Undang-Undang.
Hanya saja akan semakin membuka peluang menjamurnya jenis hubungan kerja alih daya atau outsourcing, padahal sudah terbukti bahwa bentuk hubungan triangular layaknya outsourcing ini sangat tidak menguntungkan bagi pekerja.
4. Perubahan Ketentuan Upah Minimum
Jika sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Upah Minimum dapat didasarkan pada wilayah provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK), serta upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota (Upah Minimum Sektoral), maka ketentuan ini tidak lagi berlaku dalam RUU Cipta Kerja.
RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa diantara Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan akan disisipkan 7 (tujuh) pasal tambahan, salah satunya adalah Pasal 88C yang berbunyi: (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.
Artinya, jika RUU disetujui, maka tidak akan ada lagi Upah Minimum Kabupaten/Kota maupun Upah Minimum Sektoral, karena Upah Minimum yang berlaku hanyalah Upah Minimum Provinsi.
Masalahnya, tidak ada alasan yang mendasari penghapusan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral ini. Selama ini UMK dan Upah Minimum Sektoral wajib dipatok lebih tinggi dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi.
Hal baru lain yang ditawarkan oleh RUU Cipta Kerja adalah adanya Upah Minimum Padat Kerja yang berpotensi menimbulkan polemik karena pengaturannya yang ambigu. RUU Cipta Kerja hanya menyebutkan bahwa upah minimum industri padat kerja dihitung dengan menggunakan formula tertentu.
Tidak ada penjelasan mengenai hal ini kecuali ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya, lagi-lagi memperpanjang alur pengaturan upah minimum ke ketentuan yang lain, yang mana berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum.
5. Istilah Ambigu dalam Pemberian Cuti
Kritik lain bagi RUU Cipta Kerja adalah adanya pasal-pasal yang rentan menimbulkan misinterpretasi karena menggunakan istilah yang ambigu. Sebagai contoh, Pasal 93 ayat (2) RUU Cipta Kerja yang akan mengubah Pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pengecualian dari asas ‘no work no pay’.
Pasal ini menyebutkan bahwa “pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan”. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ‘berhalangan’ baik dalam pasal tersebut, maupun dalam penjelasan pasal.
Padahal, kata ‘berhalangan’ memiliki arti yang luas, sehingga rawan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pemberian hak cuti bagi pekerja. Ketika kata ‘berhalangan’ berintepretasi bebas maka perlindungan hak cuti bagi pekerja menjadi tidak terjamin.
Ketidakjelasan pemilihan kata dalam Pasal 93 ayat (2) RUU Cipta Kerja dikhawatirkan justru akan berpotensi menghapuskan hak pekerja termasuk pekerja perempuan mendapatkan cuti sakit, cuti haid, cuti melahirkan, maupun cuti menikah dan menikahkan.
6. Perubahan Konsep Pemutusan Hubungan Kerja
Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadinya berbunyi “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.” menjadi “Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh”.
Perubahan ini menghilangkan konsepsi mendasar mengenai PHK dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat dihindari.
Rumusan Pasal 151 ayat (1) di RUU Cipta Kerja juga menghilangkan peran pemerintah dalam mengupayakan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja; PHK menjadi hal yang privat di mana seluruhnya diserahkan pada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha.
Selain itu, peranan serikat buruh untuk berunding dengan pengusaha terkait dengan pemutusan hubungan kerja juga terancam hilang, karena RUU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Pasal 151 ayat (2) RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa: “Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Rumusan pasal ini membingungkan dan tidak tegas mengatur kewajiban pengusaha untuk menyelesaikan PHK melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Masih terkait dengan PHK, RUU Cipta Kerja juga memberikan keleluasaan lebih bagi pengusaha untuk melakukan PHK tanpa perlu kesepakatan dan/atau prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal: perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur); atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.
Pengecualian-pengecualian ini tidak dikenal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan berpotensi menimbulkan banyak PHK baru, utamanya terkait perusahaan yang pailit.
Pasal 156 RUU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan uang penggantian hak, menghapuskan ketentuan spesifik mengenai kompensasi untuk tiap-tiap alasan pemutusan hubungan kerja, serta mengurangi perhitungan maksimum uang penghargaan kerja.
Perubahan ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja pada akhirnya memang lebih memudahkan terjadinya PHK, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
7. Pasal Sweetener Sulit Implementasi
Dalam hal lain, pasal-pasal sweetener atau pemanis yang sebenarnya merupakan poin yang positif, namun implementasinya nanti akan sulit untuk dilakukan karena pengaturannya yang tidak jelas.
Sebagai contoh, Bagian Ketiga tentang Jenis Program Jaminan Sosial mengubah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan menambahkan ketentuan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan.
Hal lainnya adalah terkait dengan “penghargaan lainnya” yang diatur dalam Bagian Kelima tentang Penghargaan Lainnya dalam Pasal 92 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang ini memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja/buruh”.
Pemberian penghargaan lainnya ini membingungkan, karena tidak jelas komponennya. Perumusan Pasal 92 juga ambigu karena tidak jelas berapa kali pekerja berhak mendapatkan uang penghargaan lainnya, apa ketentuannya jika tidak diberikan, dan lain-lain.
Ketidakjelasan ini menyebabkan banyak pihak beranggapan bahwa pasal ini hanyalah pasal “pemanis” yang sulit untuk diimplementasikan karena pengaturannya yang ambigu.
Kesimpulan
Secara umum, policy paper tim FH UGM yang menyoroti 11 bidang dalam bahasan RUU Cipta Kerja, menarik sejumlah kesimpulan.
Pertama, RUU Cipta Kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan.
Kedua, tim menyadari bahwa menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mewujudkan pembangunan memang penting namun seyogyanya upaya ini perlu dibangun dengan tidak mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.
Ketiga, terdapat kontradiksi bahwa di satu sisi RUU ini dibuat dengan maksud untuk mengatasi permasalahan over-regulated dan over-lapping pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi. Namun di sisi lain, RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper-regulated dan pengaturan yang jauh lebih kompleks.
Keempat, partisipasi merupakan aspek penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.