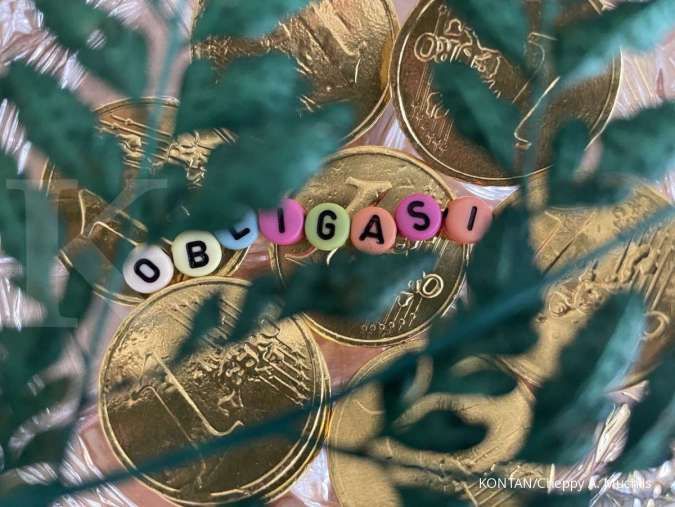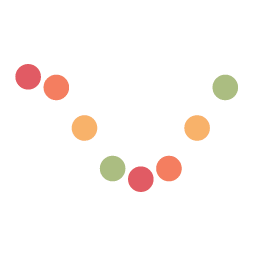KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rizki, remaja 18 tahun asal Bogor, kini bagaikan ronin dalam sejarah militer Jepang. Dia seolah seorang samurai tanpa majikan. Sampai hari ini Rizki belum juga "punya" sekolahan. Dia sudah lulus SMA –salah satu peraih nilai terbaik di sekolahnya– tapi belum diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) manapun.
Sejak hari pertama masuk SMA tiga tahun lalu, Rizki sudah mengincar kampus PTN yang dia tuju: ITB! Maka, selama sekitar 1.000 hari lebih setelahnya, segenap upaya telah dia kerahkan untuk mencapai tujuan itu. Tekun belajar hingga lewat tengah malam, jarang bermain di luar sekolah, rajin ikut bimbingan tes, hanya sebagian dari ikhtiarnya.
Sayang sekali, nasibnya tak selaras niat, ketekunan, dan semangatnya. Dia belum berhasil mendapatkan kaveling bangku kuliah lewat jalur prestasi akademik (SNBP) maupun jalur ujian tertulis (SNBT).
Saat ini mungkin ratusan ribuan remaja di Indonesia bernasib serupa Rizki. Niat, semangat, dan ketekunan menggebu; namun belum kebagian bangku kuliah di kampus impian. Banyak sebab yang membuat mereka menjadi "ronin", dari faktor ekonomi keluarga, kemampuan akademis, keterbatasan wawasan memilih kampus, hingga tentu saja persaingan yang sangat ketat.
Pada UTBK 2025 lalu terdapat 860.976 individu yang bersaing memperebutkan 259.564 bangku kuliah. Bahkan ditambah daya tampung jalur mandiri 185.952 kursi, total kapasitas PTN masih jauh dari cukup dibanding total lulusan SMA/SMK yang ingin kuliah.
Tentu saja banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang siap menyodorkan kursi untuk menampung para remaja yang tidak beruntung itu. Tapi, biasanya, orang tua mereka yang mendaftar belakangan setelah gagal menembus PTN harus menanggung biaya lebih besar. Akibatnya tak semua peminat kuliah yang gagal menembus PTN akan otomatis mendaftar di PTS.
Ingat, di luar jumlah mereka yang gagal mengakses bangku kuliah, masih banyak lagi yang sejak awal memang tidak mau dan tidak mampu kuliah. Jadi, bisa kita bayangkan berapa banyak siswa yang harus puas berijazah setingkat SMA dan SMK? Lebih ironis lagi, drama seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Berlimpah SDM berusia produktif akan tampak sebagai bonus jika kita lihat dari kacamata industrialis. Namun, tanpa investasi memadai terhadap "bonus" tersebut, sama saja kita mewariskan beban demografi bagi generasi di masa depan.