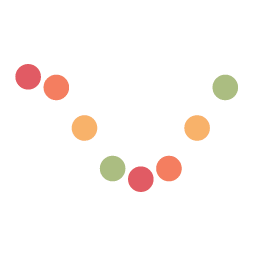KONTAN.CO.ID - Perang Rusia–Ukraina mendorong naik harga minyak mentah dari US$ 75 per barel di akhir 2021 hingga sempat menyentuh US$ 120 per barel. Di akhir Agustus, harga minyak mulai turun ke US$ 87, menyisakan kenaikan sekitar 26% sejak awal tahun.
Di saat yang sama, konsumsi bahan bakar meningkat seiring pembukaan aktivitas ekonomi. Akibatnya alokasi subsidi BBM pemerintah membengkak dan berpotensi melebihi rencana anggaran. Wacana kenaikan harga BBM pun mengemuka.
Sejak tahun 2000, tercatat Indonesia sudah mengalami kenaikan harga BBM sembilan kali. Dampak kenaikan BBM tidak selalu negatif, sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi.
Pada pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid, sekitar tahun 2000, harga BBM pernah naik signifikan dan membuat inflasi melonjak. Ini menekan IHSG lantaran saat itu emiten di bursa juga masih terdampak krisis moneter tahun 1998, terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.
Pada pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri harga BBM kembali naik. Meski inflasi tinggi, namun pertumbuhan ekonomi yang lebih baik mengurangi efek kenaikan BBM, sehingga IHSG masih positif.
Di pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seiring gejolak harga minyak, pemerintah mengambil keputusan menaikkan harga BBM dua kali hingga 150% dan membuat inflasi meroket hingga 17%. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di atas 5% dan IHSG bertahan positif.
Di 2008, pemerintah kembali menaikkan harga BBM dan mendorong inflasi naik tinggi. Tahun ini juga terjadi krisis subprime mortgage yang memukul IHSG terkoreksi sangat dalam.
Kenaikan BBM kembali tidak terhindarkan di awal pemerintahan presiden Joko Widodo. Tapi saat itu kenaikan BBM dipandang positif untuk mengurangi subsidi yang kemudian dialihkan mendanai pembangunan infrastruktur (lihat tabel).
|
Kenaikan BBM Premium dan Dampaknya Terhadap Inflasi Serta IHSG |
||||||
|
Tahun |
Dari |
Menjadi |
∆% |
Inflasi |
Pertumbuhan Ekonomi |
Return |
|
2000 |
600 |
1.150 |
91,70% |
9,40% |
0,90% |
-38,00% |
|
2001 |
1.150 |
1.450 |
26,00% |
12,60% |
3,80% |
-4,40% |
|
2002 |
1.450 |
1.550 |
7,00% |
10,00% |
4,30% |
8,40% |
|
2003 |
1.550 |
1.810 |
17,00% |
5,20% |
4,90% |
62,80% |
|
2005 |
1.810 |
2.400 |
32,60% |
17,10% |
5,70% |
16,20% |
|
2005 |
2.400 |
4.500 |
87,50% |
|||
|
2008 |
4.500 |
6.000 |
33,30% |
11,10% |
6,00% |
-50,00% |
|
2008 |
6.000 |
5.500 |
-8,30% |
|||
|
2008 |
4.500 |
5.000 |
-9,10% |
|||
|
2009 |
5.000 |
4.500 |
-10,00% |
2,80% |
4,50% |
87,00% |
|
2014 |
4.500 |
6.500 |
44,00% |
8,40% |
5,00% |
22,30% |
|
2019* |
6.500 |
7.650 |
17,70% |
2,70% |
5,00% |
1,70% |
|
Ket: *pada tahun ini bensin jenis premium mulai digantikan oleh jenis pertalite |
||||||
Dari tabel di atas maka dapat dicermati kenaikan BBM tidak serta merta akan merontolkan pasar saham. Kenaikan inflasi yang diikuti dengan kenaikan suku bunga lebih berpengaruh negatif pada pasar obligasi. Investor saham masih tetap akan melihat pertumbuhan penjualan dan laba emiten.
Jadi, bila harga BBM naik lagi, investor jangka pendek dengan risk profile konservatif memang sebaiknya fokus pada instrumen pasar uang. Investor jangka menengah hingga tiga tahun dapat memanfaatkan penurunan harga obligasi untuk mendapatkan yield yang menarik. Bagi investor jangka panjang, investasi pada saham masih dapat menguntungkan sepanjang pertumbuhan ekonomi terjaga dan koreksi yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness.