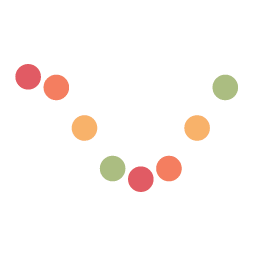KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Siapa tidak kenal Sir Isaac Newton yang jenius? Dia adalah pakar fisika dan matematika Inggris ternama. Temuan-temuannya seperti kalkulus dan hukum gravitasi, turut mengubah dunia.
Tapi, kepintaran bukan jaminan bakal sukses berinvestasi saham. Musim semi tahun 1720, atau ketika Newton berusia sekitar 78 tahun, dia memiliki saham South Sea Company, saham yang paling panas di Inggris saat itu.
South Sea adalah perusahaan yang diberi hak monopoli oleh pemerintah Inggris untuk perdagangan di Amerika Selatan. Hak monopoli ini menarik para investor saham. Akibatnya, harga saham awal di sekitar 100 bergerak naik secara cepat.
Saat harganya sekitar 150, Newton bereksperimen membeli sedikit saham. Beberapa bulan kemudian, ketika harga saham sudah menjadi dua kali lipat, dia menjual sahamnya. Namun harga saham South Sea naik terus. Newton saat itu iri melihat sahabat-sahabatnya menjadi kaya raya saat saham South Sea menyentuh harga 500 per saham.
Dia pun membeli kembali saham South Sea dengan jumlah yang jauh lebih banyak saat harga sudah mencapai 700. Harga South Sea naik hingga 950 dalam waktu tiga bulan, tetapi Newton belum mau menjualnya karena mengharapkan profit lebih besar.
Celakanya, harga saham kemudian terjun bebas kembali ke level semula, sekitar 100 dalam waktu 6 bulan. Dengan berat hati, Newton terpaksa jual rugi (cut loss).
Rute perjalanan emosional Newton adalah sebagai berikut: dari ketamakan ke kepuasan. Kemudian, dari iri hati dan ketamakan yang lebih besar, berakhir dengan penderitaan.
Total Newton rugi 20.000 atau sekitar Rp 300 juta rupiah. Hampir seluruh tabungannya habis. Kata Newton dengan getir, "I can calculate the movement of the stars, but not the madness of men".
Gelembung saham pernah terjadi pada investor saham Amerika Serikat. Mereka mengalami Dot-com bubble (juga disebut Tech bubble atau Internet bubble).
Ini adalah fenomena bubble (gelembung) di pasar saham yang disebabkan oleh tindakan spekulasi pada saham internet dan telekomunikasi.
Antara periode 1995 hingga Maret 2000, Indeks Nasdaq yang berisikan saham-saham internet dan teknologi mencatat kenaikan 400%, menjadi 5.042! Dari titik tertinggi tersebut, indeks Nasdaq jatuh 78% selama periode Maret 2000 hingga Oktober 2002, Penurunan ini menghanyutkan US$ 5 triliun uang investor.
Pada akhir 2001, mayoritas gelembung saham internet pecah. Bahkan saham teknologi bluechip seperti Cisco, Intel, dan Oracle turun 80%.
Setidaknya dibutuhkan waktu 15 tahun bagi Indeks Nasdaq kembali ke level 5.000. Bayangkan nasib investor yang beli saham teknologi dipucuk dan tidak cut loss.
Hal yang sama pernah terjadi di China. Pada Juli 2015, kepanikan melanda pasar modal China. Pemerintah China yang tadinya mendorong orang untuk membeli saham, tiba-tiba panik menghentikan investor saham yang panik menjual sahamnya.
Bagaimana tidak, indeks harga saham di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen dalam waktu sebulan, telah turun 32% sejak 12 Juni 2015. Duit investor saham yang menguap akibat stock market crash tersebut adalah US$ 3,2 triliun!
Sebelumnya, indeks harga saham di kedua pasar saham China tersebut naik 150% selama kurun waktu Juli 2014 hingga 12 Juni 2015. Tekanan jual yang begitu deras membuat 1.300 emiten menghentikan transaksi sahamnya, membekukan nilai saham sebesar US$ 2,7 triliun atau sekitar 40% dari kapitalisasi pasar saham China.
Financial atau stock market bubble terbentuk ketika harga saham melambung jauh di atas nilai wajarnya. Setidaknya, ada dua faktor penyebab utama.
Pertama, psikologi sosial. Misalnya, "herding", yakni kecenderungan investor mengikuti tindak-tanduk kelompok (crowd).
Tak dipungkiri, pelaku pasar cenderung mencari cara mudah dalam memilih saham. Antara lain, memilih saham yang sedang populer atau diminati banyak orang. Tindakan ini bisa mendorong harga sebuah saham naik tinggi dalam waktu singkat, yang akhirnya semakin mendorong investor lain untuk ikut membeli.
Bayangkan jika ada orang yang bertindak sebagai lokomotif yang menggerakan harga sebuah saham sembari "mem-pom pom" saham tersebut lewat sosial media. Setelah lokomotif bergerak, otomatis gerbongnya akan mengikuti.
Kedua, keserakahan (greed) dan ketakutan (fear) para pelaku pasar. "Keserakahan" mendorong tindakan spekulatif para pelaku pasar yang ingin dapat cuan besar secara cepat. Di sisi lain, disertai "ketakutan" akan kehilangan kesempatan meraup keuntungan besar.
Ketakutan akan kehilangan kesempatan atau fear of missing opportunity (FOMO) ini juga yang membuat pelaku pasar lainnya ikut berspekulasi di saham yang sedang meroket harganya. Dalam kasus dot.com bubble, sejatinya mayoritas investor saham teknologi tidak paham model bisnis saham yang dia beli. Mereka beli karena ikut-ikutan sensasi (hype) dan terkena virus FOMO.
Pada tingkat ketidakrasionalan yang tinggi serta dorongan ingin cepat kaya, mereka berani membeli saham yang harganya sudah sampai di bulan. Mungkin dengan harapan harga masih bisa terbang ke planet Mars. Yang terjadi adalah harganya malah crash kembali ke bumi.
Dari pengalaman ini, tampaknya kita perlu mengigat pesat dari Warren Buffett. Dia pernah memberikan nasihat bahwa jika investor tidak bisa mengendalikan emosinya, dia tidak akan menjadi investor yang sukses. Setidaknya Newton sang jenius pun ikut berkontribusi mengamini petuah Buffett ini.