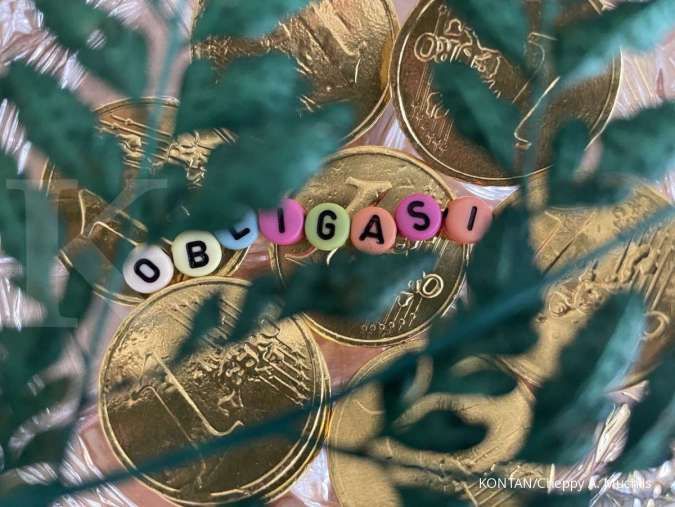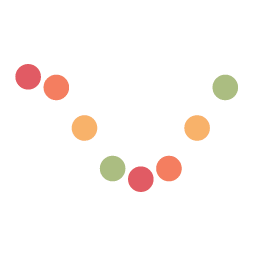KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas, kali ini bergerak dari tarif impor menuju sanksi korporasi, pelabuhan, hingga kontrol bahan baku strategis. Kedua negara tampak membuka palagan baru di jalur laut dan rantai pasok global, yang kini menjadi arena tarik-menarik kekuatan ekonomi.
Langkah China menjatuhkan sanksi terhadap lima konglomerasi Korea Selatan yang punya hubungan bisnis dengan Amerika—menandai strategi Beijing memperluas tekanan ke mitra sekutu Washington. China juga membalas kebijakan tarif pelabuhan AS dengan mengenakan biaya setara 400 yuan per ton bagi kapal milik atau dioperasikan entitas AS. Laut menjadi simbol perang ekonomi baru. Kebijakan saling balas tarif antara dua ekonomi terbesar dunia langsung mengguncang sentimen global. Indeks saham utama di Wall Street dan Asia sempat berfluktuasi tajam seiring kekhawatiran investor terhadap disrupsi rantai pasok dan lonjakan harga bahan baku industri.
IMF memang masih menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2%, namun lembaga itu memperingatkan bahwa jika eskalasi perang dagang berlanjut, pertumbuhan dunia dapat terkoreksi hingga 1,8 poin persen. Artinya, efek domino ke pasar finansial bukan lagi ancaman retorik.
Investor kini memutar strategi: beralih ke aset aman seperti emas, dolar AS, dan obligasi pemerintah Jepang. Lonjakan harga komoditas kritis seperti nikel, litium dan terutama rare earth mulai terlihat sejak China mengumumkan pembatasan ekspor logam tanah jarang yang digunakan dalam chip, kendaraan listrik, dan senjata canggih.
China secara terbuka menjadikan kontrol atas rare earth sebagai alat tawar geopolitik. Mulai 1 Desember 2025 ekspor bahan mentah dan produk turunan logam tanah jarang akan dibatasi secara ketat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap ancaman tarif 100% dari pemerintahan Trump terhadap seluruh impor dari China. Bagi Beijing, ini bukan sekadar pembalasan. Langkah itu merupakan pesan strategis: dunia masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku teknologi dari China. Bagi Washington, ancaman ini menuntut diversifikasi cepat -- entah melalui aliansi baru di Asia Tenggara, Amerika Latin, atau investasi besar-besaran di sektor tambang domestik.
Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan situasi ini. Banyak korporasi global kini mencari lokasi produksi alternatif di luar China untuk menghindari risiko tarif tinggi. Jika Indonesia mampu mempercepat reformasi industri, penyederhanaan izin, dan insentif investasi hijau, maka negeri ini bisa menjadi destinasi manufaktur pengganti bagi produk elektronik, tekstil dan otomotif.