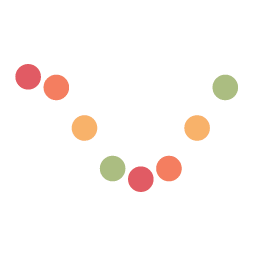KONTAN.CO.ID - Di mata investor saham Indonesia, tiada dekade berlalu tanpa datangnya krisis. Itulah yang terjadi dalam seperempat abad terakhir, yaitu tahun 1998, 2008, dan 2020. Seberapa berat kita melewatinya, inilah cerita singkatnya.
Untuk kisah lebih lengkapnya, Anda bisa membaca buku "Melintasi 3 Krisis Multidimensi" terbitan Kontan.
Krisis Moneter 1998
Krisis keuangan 1998 yang berawal dari Thailand pada Juli 1997, lalu menyebar ke Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Filipina dan beberapa negara lain, telah meruntuhkan perbankan dan rupiah kita. Perekonomian kawasan Asia pun rontok. Negara kita terdampak sangat parah.
Kurs rupiah merosot 83,3% dari Rp 2.500 per dollar AS di medio 1997 menjadi Rp 15.000 di 1998. Harga barang impor melonjak beberapa kali lipat sehingga inflasi melambung 77% pada 1998.
Pertumbuhan ekonomi yang di 1997 masih naik 4,7% terjun bebas menjadi minus 13%. Tiga indikator utama perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar, semuanya sangat buruk dan terjelek setelah periode 1965-1966.
Baca Juga: Manufaktur Uni Eropa Mulai Bergeliat, Efek Hambatan Rantai Pasokan Melonggar
Faktor utama keterpurukan ini adalah banyaknya utang pemerintah dan korporasi dalam valuta asing. Sementara cadangan devisa dan PDB hanya US$ 19 miliar dan US$ 95 miliar. Bandingkan dengan posisi saat ini, masing-masing US$ 146 miliar dan US$ 1,1 triliun.
Tidak sedikit emiten yang rugi triliunan rupiah akibat selisih kurs di 1998. Sebanyak 160 bank dari 234 bank yang ada saat itu tidak bisa memenuhi kewajiban ke bank lain, seperti kalah kliring. Puluhan bank dibekukan operasinya atau dilikuidasi dan lainnya harus diselamatkan dengan BLBI.
Saham 32 bank yang sudah listed saat itu semuanya dihargai puluhan hingga ratusan rupiah. Sebanyak 21 saham masih bertahan hingga setahun kemudian, tapi hanya belasan saja yang akhirnya survive.
Bagaimana dengan IHSG? Jika pertumbuhan ekonomi negatif, secara fundamental, pergerakan indeks bursa saham di negara itu pun akan ikut negatif. IHSG yang sempat mencapai 740,8 pada 8 Juli 1997 merosot ke 256,8, anjlok 65,3% pada 21 September 1998.
Karena volatilitas saat itu bersifat fundamental, IHSG perlu waktu 5-6 tahun untuk kembali ke posisi sebelum krisis. IHSG baru dapat menembus angka 741 di Januari 2004.
Krisis Subprime Mortgage 2008
Pasar modal kita kembali mengalami krisis di 2008. Tutup di angka 2.746 di akhir 2007, secara perlahan IHSG longsor 60,7% ke 1.111 pada 28 Oktober 2008, sebelum ditutup di angka 1.355 pada akhir tahun itu.
Baca Juga: Ekonomi Turki 2021 Terburuk Hampir Dua Dekade Terakhir, Inflasi Tertingi, Lira Anjlok
Tidak hanya di pasar saham, tekanan berat juga menghantam obligasi global pemerintah. Akibat minimnya cadangan devisa yang hanya sekitar US$ 50 miliar dan kurs rupiah yang merosot hingga Rp 12.000 per dollar AS, obligasi pemerintah dalam dollar AS kena cornering, hingga harus memberi kupon 11,625% dengan yield 11,75% p.a. untuk tenor 10 tahun di Maret 2009. Saya sempat menikmati gurihnya yield tinggi ini, plus capital gain 45% di Desember 2009.
Berbeda dengan krisis Asia di 1998, krisis di 2008 sejatinya adalah krisis yang dipicu kredit pemilikan rumah (mortgage) untuk warga kelas dua (subprime) di AS, tetapi dengan cepat menjalar ke pelosok dunia. Seluruh bursa saham jatuh sehingga kapitalisasi pasar global terpangkas 47,6% dari US$ 60,9 triliun di 2007 menjadi US$ 31,9 triliun di akhir 2008.
BEI juga tidak luput. Sepanjang 2008, total kapitalisasi pasar di BEI susut jadi Rp 1.076 triliun, dari Rp1.988 triliun.
Namun krisis 2008 sejatinya bukan krisis kita, karena tidak memukul sektor riil. Pertumbuhan ekonomi di 2008 masih mencapai 6% dan turun menjadi 4,5% di 2009. Karenanya, IHSG naik 87% dan 46% di 2009 dan 2010. Rupiah juga menguat kencang hingga Rp 8.450 per dollar AS akibat boom harga komoditas pada 2011.
Pandemi 2020
Kecepatan penurunan harga saham di dua krisis sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan tahun 2020. IHSG terjun bebas tanpa perlawanan berarti selama hampir tiga minggu, hingga terkapar di 3.938 pada 24 Maret 2020 dari 6.300 di awal tahun (turun 37,5%). Ini masih lebih baik dibandingkan indeks LQ45 yang jatuh 44,1% dalam tiga bulan dari 1.014,5 ke 566,8.
Baca Juga: Larangan Ekspor Batubara Indonesia Ancam Pasokan Energi Sejumlah Negara Ekonomi Besar
Di 1998 dan 2008 juga tidak terjadi banyak auto reject bawah (ARB) dibanding 2020. Baru kali ini empat bank berkapitalisasi terbesar mengalami ARB alias tidak ada volume bid pada saat bersamaan. Tidak ada seorang pun yang mau membeli saham BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI pada harga yang sudah turun maksimal pada hari itu. Ini mungkin tidak akan pernah terjadi lagi.
Seperti dua krisis lainnya, rupiah kembali merosot ke titik terendahnya yaitu Rp16.915 pada 24 Maret 2020 dari Rp 14.000 di akhir Februari 2020. Salah satu penyebab utama memburuknya indeks dan kurs rupiah adalah keluarnya dana asing dari pasar keuangan, sebesar Rp 125 triliun, untuk dipindahkan ke safe haven seperti emas dan dollar Amerika Serikat, akibat merebaknya Covid-19.
Berbeda dengan dua krisis sebelumnya, krisis kali ini disebabkan pandemi dan terjadi secara global. Karena pertumbuhan ekonomi hanya negatif 2,1%, IHSG cuma perlu setahun untuk kembali ke 6.300. Pertumbuhan investor domestik dari kalangan milenial dan ibu rumahtangga dengan aura optimisme barunya mempercepat resiliensi bursa saham dalam negeri.
Selamat Tahun Baru 2022 bagi para pembaca setia. Semoga pertumbuhan ekonomi tahun ini menembus 6%, sehingga IHSG bisa melesat, minimal 10% seperti di 2021.