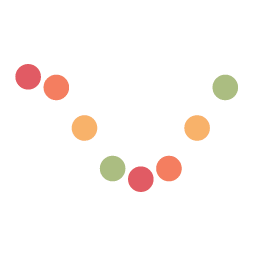Orang Muda di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2025 menjadi penanda yang getir dalam peta perjalanan sosial-ekonomi Indonesia. Nyaris semua lini kehidupan merasakan denyut krisis -- dari pengambil kebijakan hingga buruh lapangan, dari ruang Istana sampai emperan trotoar. Ketegangan sosial-ekonomi seolah menjadi muatan tetap dalam setiap berita harian, membentuk narasi kolektif tentang betapa rapuhnya keseimbangan hidup warga negara. Tapi jika ada kelompok yang paling berisik dalam diam, paling banyak menghela napas namun paling jarang didengar, maka itu adalah orang muda.
Ketika data menjadi jendela awal memahami kompleksitas, kita dihadapkan pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 yang mencatat 7,28 juta orang menganggur, atau sekitar 4,76% dari total angkatan kerja. Meski secara persentase terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, secara nominal pengangguran justru bertambah. Fenomena ini memperlihatkan satu hal: perbaikan indikator makro bukan jaminan perbaikan kesejahteraan mikro. Apalagi jika kita menggali lebih dalam, bahwa lapangan pekerjaan yang tercipta bukanlah lapangan yang stabil, layak dan produktif.
Baca Juga: Jaga Whistleblower Aman, Bisnis pun Berkelanjutan
Ambil contoh kasus yang baru-baru ini mencuat: Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang dipadati oleh 25.000 pencari kerja. Dalam kerumunan itu, kita menyaksikan lebih dari sekadar antrean panjang dan ribuan CV. Kita menyaksikan harapan yang ditumpuk, kecemasan yang disembunyikan, dan keringat yang menjadi simbol ketidakpastian. Jakarta, sebagaimana disebut Harian Kompas edisi 22 Juni 2025, memang menjadi "gula-gula" yang menggoda, namun manisnya hanya untuk segelintir. Sementara ribuan lainnya harus rela menggigit pahitnya realitas: biaya hidup tinggi, lapangan kerja sempit dan tekanan sosial yang tiada henti.
Kelas menengah
Data BPS menunjukkan bahwa mayoritas kelas menengah Indonesia adalah orang muda: Generasi Milenial (24,60%), Gen Z (24,12%), dan Gen Alpha (12,77%). Namun pertanyaan pentingnya: apakah menjadi bagian dari kelas menengah berarti aman dari guncangan ekonomi? Jawabannya, jelas tidak. Sebaliknya, kelompok ini justru paling rentan. Mereka tidak miskin secara "administratif," tetapi secara struktural sangat rapuh. Mereka sering disebut sebagai sandwich generation -- harus menghidupi diri sendiri, membiayai orang tua, dan mulai menyiapkan masa depan anak-anak.
Baca Juga: Mencari Peluang Cuan Di Tengah Risiko Menantang
Orang muda kini hidup dalam logika "survival mode." Jangankan menabung atau investasi, bertahan hidup saja sudah menjadi perjuangan. Gaji dipakai untuk biaya kos, transportasi, makan, tagihan dan jika sempat -- biaya eksistensi sosial agar tak tersisih dari lingkaran komunitas. Jika ada sisa, itu pun mungkin hanya cukup untuk membeli diskon. Maka, seperti yang pernah ditulis Chatib Basri dalam opininya di Harian Kompas (24/7/2024) bahwa: "Instrumen perlindungan sosial dan lapangan kerja kelas menengah memang perlu dipikirkan. Mereka tak tergolong miskin, namun guncangan ekonomi dapat mengantar mereka pada kemiskinan. Hidup kelas menengah memang tak mudah. Ia butuh keterampilan untuk menganggap 'diskon' sebagai bentuk kekayaan dan 'belanja hemat' sebagai prestasi."
Jeritan orang muda bukan hanya akibat dari dinamika ekonomi global. Ada persoalan mendalam dalam desain struktural kebijakan kita. Pendidikan tinggi belum selaras dengan kebutuhan industri. Lulusan sarjana membanjiri pasar kerja tanpa keterampilan yang sesuai dengan permintaan. Sementara itu, sektor informal menjadi penampung terbesar, tapi tanpa perlindungan dan kejelasan masa depan.
Baca Juga: Kinerja Keuangan Bank Milik Investor Korea Belum Menggembirakan
Di sisi lain, instabilitas ketenagakerjaan juga diperparah oleh gelombang PHK di sektor teknologi, manufaktur dan ritel. Banyak orang muda yang sebelumnya merasa sudah "mapan" justru harus kembali ke titik nol. Ini bukan sekadar kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan arah hidup. Sense of security yang selama ini dipinjam dari gaji bulanan tiba-tiba lenyap, meninggalkan kegelisahan eksistensial.
Menyelamatkan
Dalam tulisan saya sebelumnya di Harian Kompas edisi 12 Maret 2025 berjudul Tingginya Animo Menjadi ASN dan Beban Berat Birokrasi, saya menggarisbawahi bagaimana meningkatnya ketergantungan pada formasi ASN menjadi cerminan ketidakmampuan sektor swasta menciptakan pekerjaan yang aman dan menjanjikan. Pemerintah seakan menjadi satu-satunya harapan. Namun membuka formasi ASN besar-besaran jelas bukan solusi. Anggaran negara akan tergerus untuk membayar gaji birokrat, bukan untuk belanja pembangunan atau subsidi produktif.
Baca Juga: Kasus Fraud Startup Akibat Dikejar Target Untung
Jika lapangan kerja publik menjadi pelarian, maka kita sedang menyaksikan distorsi ekonomi yang kronis. Idealnya, peran negara adalah sebagai enabler -- penyedia infrastruktur, penguat pasar tenaga kerja, bukan sebagai satu-satunya penyerap tenaga kerja. Kita butuh kebijakan yang mampu menumbuhkan sektor produktif, memberdayakan UMKM, dan menstimulus industri kreatif, serta ekonomi yang memberi ruang bagi kreativitas orang muda.
Pemerintah harus segera meninggalkan pendekatan kebijakan yang sekadar bersifat populistik, dan mulai membangun kebijakan struktural yang adil dan futuristik. Beberapa langkah penting yang perlu diprioritaskan: reformasi sistem pendidikan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial untuk kelas menengah, pengembangan ekosistem ekonomi baru, desentralisasi akses dan informasi pekerjaan.
Jika orang muda hari ini hanya dibekali dengan semangat tanpa sistem pendukung yang memadai, maka mereka akan tetap terjebak dalam siklus survival mode yang panjang. Mereka bukan hanya akan kehilangan harapan, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk berkontribusi bagi negara. Dan jika kita gagal menyelamatkan orang muda hari ini, maka kita sesungguhnya sedang gagal menyelamatkan masa depan republik ini.
Baca Juga: Pelaku Kripto Berharap OJK Lebih Terbuka Terhadap Inovasi
Sudah saatnya kebijakan negara berpihak, bukan hanya hadir. Bukan lagi saatnya membahas angka kemiskinan dengan indikator administratif, tetapi dengan realitas kehidupan yang semakin brutal dan menuntut respons yang cerdas. Jangan sampai orang muda kita mengalami fenomena "mati segan, hidup tak mau," akibat persoalan sistemik yang semakin lama semakin parah dan tidak pernah benar-benar dibenahi.
Kebijakan yang adil
Sebagaimana pernah dipaparkan oleh Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu prasyarat utama agar Indonesia dapat bertransformasi menjadi negara maju adalah dengan memastikan dominasi struktur demografisnya diisi oleh kelompok kelas menengah yang kuat -- bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas. Kelas menengah diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional melalui daya beli yang stabil, pola konsumsi yang produktif, serta partisipasi aktif dalam pembangunan. Namun, cita-cita itu agaknya semakin menjauh jika kita jujur menatap realita hari ini.
Baca Juga: Ujian Daya Saing Produk Indonesia di ASEAN
Alih-alih menjadi penggerak kemajuan, kelas menengah justru semakin banyak yang terjebak dalam kemiskinan struktural -- suatu kondisi di mana individu tidak secara formal tercatat sebagai miskin, tetapi tidak memiliki cukup sumber daya, akses, dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan. Mereka hidup dalam ilusi kesejahteraan, namun di baliknya tersembunyi beban pengeluaran tinggi, ketidakpastian pekerjaan, hingga tekanan sosial yang menggerus daya tahan mental.
Refleksi ini membawa kita pada kesimpulan bahwa transformasi menuju negara maju tidak akan pernah terwujud jika kelas menengahnya dibiarkan rapuh, tanpa perlindungan, dan tanpa ruang untuk tumbuh. Maka, satu-satunya jalan yang realistis dan bermartabat adalah melalui kehadiran negara yang adil, aktif dan inklusif dalam menyelamatkan serta memperkuat kelompok ini.
Baca Juga: Pasar Sawit Indonesia ke Eropa Kian Licin
Negara harus membangun kembali kontrak sosial antara pemerintah dan warga muda kelas menengah -- dengan cara menyediakan kebijakan yang berpihak pada pemerataan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja yang bermakna. Sebab tanpa kelas menengah yang sehat, stabil dan optimis, maka impian Indonesia Emas 2045 akan tinggal menjadi slogan kosong yang kehilangan pijakan.